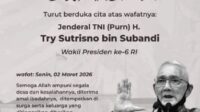Pada tahun 1992 seorang penulis di majalah the nation menggunakan kata post truth dalam tulisannya, ia dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan kata tersebut. Post truth mengacu kepada sebuah kondisi dimana orang-orang tidak lagi peduli dengan kebenaran yang sesungguhnya, keyakinan mereka tentang kebenaran lebih dipengaruhi oleh emosi dan perasaan, sederhananya suatu informasi dianggap benar bila sesuai dengan kondisi perasaan yang ia alami namun bila tidak maka ia akan menolak dan menilai salah informasi tersebut.
Contohnya dalam praktik politik seseorang yang sudah mendukung dan mengkampanyekan kandidat tertentu maka semua informasi yang menguntungkan kandidat akan dianggap benar, sebaliknya semua informasi yang merugikan kandidat serta merta dianggap salah, tidak ada lagi proses cek kebenaran terhadap informasi tersebut, akibatnya kebenaran yang sesungguhnya tidak pernah terungkap.
Anthony Clifford Grayling seorang filsuf Inggris mengungkapkan era post truth dimulai pada tahun 2008, saat itu terjadi krisis ekonomi global yang akut, akibatnya muncul kebencian di tengah masyarakat terhadap dunia ekonomi dan politik, ekonomi dibenci karena sedang suram sedangkan politik dinilai berkontribusi memperparah situasi ekonomi. Dalam perkembangannya kata post truth lebih sering digunakan dalam dunia politik, kata ini menjadi semakin populer ketika ramai perbincangan seputar keanggotaan Uni Eropa di United Kingdom dan saat Donald Trump maju sebagai Calon Presiden pada 2016.
Dalam konteks Indonesia era post truth semakin nampak jelas saat media sosial memainkan peran penting dalam kampanye politik dari level pilkada hingga pilpres. Kehadiran media sosial dalam gelanggang politik berkontribusi pada pesatnya produksi hoax, situasi ini semakin memperparah dinamika politik di era post truth, sangat sering terjadi pendukung kandidat tertentu dengan mudah mempercayai hoax sepanjang hoax tersebut menguntungkan kandidatnya.
Bahkan bukan hanya mempercayai tetapi juga turut menyebarkan hoax tersebut, inilah titik dimana manusia yang merupakan makhluk politik lebih percaya pada kebohongan dibandingkan kebenaran itu sendiri. Kebenaran seolah tidak lagi punya makna dalam kehidupan politik, terlebih bila kebenaran tersebut tidak menguntungkan kepentingan politiknya.
Masalah menjadi semakin serius karena dalam praktik politik terkini termasuk pilpres, hoax tidak lahir dari faktor ketidaksengajaan atau kurangnya ketelitian dalam memverifikasi informasi, justru hoax sengaja dibuat untuk menyerang kelompok politik tertentu, gelontoran dana dikerahkan untuk memproduksi hoax dengan menggunakan buzzer bayaran yang beroperasi di dunia maya, jelas ini merupakan bisnis kebohongan.
Kebohongan telah menjadi komoditas bisnis yang merugikan manusia bukan hanya di bidang politik tetapi dalam semua aspek kehidupan. Bisa dibayangkan betapa suramnya masa depan politik Indonesia bila ternyata suatu waktu pilpres hanya menghasilkan pemimpin yang dipilih karena bantuan hoax. Ini tidak boleh terjadi, kita mesti memastikannya.
Era post truth yang melibatkan media sosial dalam kancah politik hanya bisa dinetralisir dengan dua cara. Pertama, kesadaran verifikasi informasi, banjir informasi yang terjadi di abad ini mengharuskan setiap orang untuk mengecek setiap informasi terlebih dahulu sebelum memberikan penilaian benar salah terhadap informasi tersebut, jemari manusia mesti dikontrol agar tidak bergerak lebih cepat dibandingkan akal sehat. Kedua, penguatan etika politik.
Benar bahwa politik tidak mungkin lepas dari kepentingan untuk berkuasa, namun perlu diingat bahwa politik juga memiliki etika dalam menapaki tangga kekuasaan. Etika politik akan memungkinkan seseorang untuk secara sadar menggunakan cara yang benar dalam berpolitik, termasuk tidak menggunakan hoax sebagai jurus pemenangan. Memang tidak mudah menerapkannya karena kekuasaan sungguh sangat menggoda, tapi perlu diingat bahwa mereka yang meraih kekuasaan dengan cara yang salah dan kejam biasanya juga akan terjungkal dari kekuasaan dengan cara yang kejam pula.
Penulis: Zaenal Abidin Riam
Pengamat Kebijakan Publik/Koordinator Presidium Demokrasiana Institute